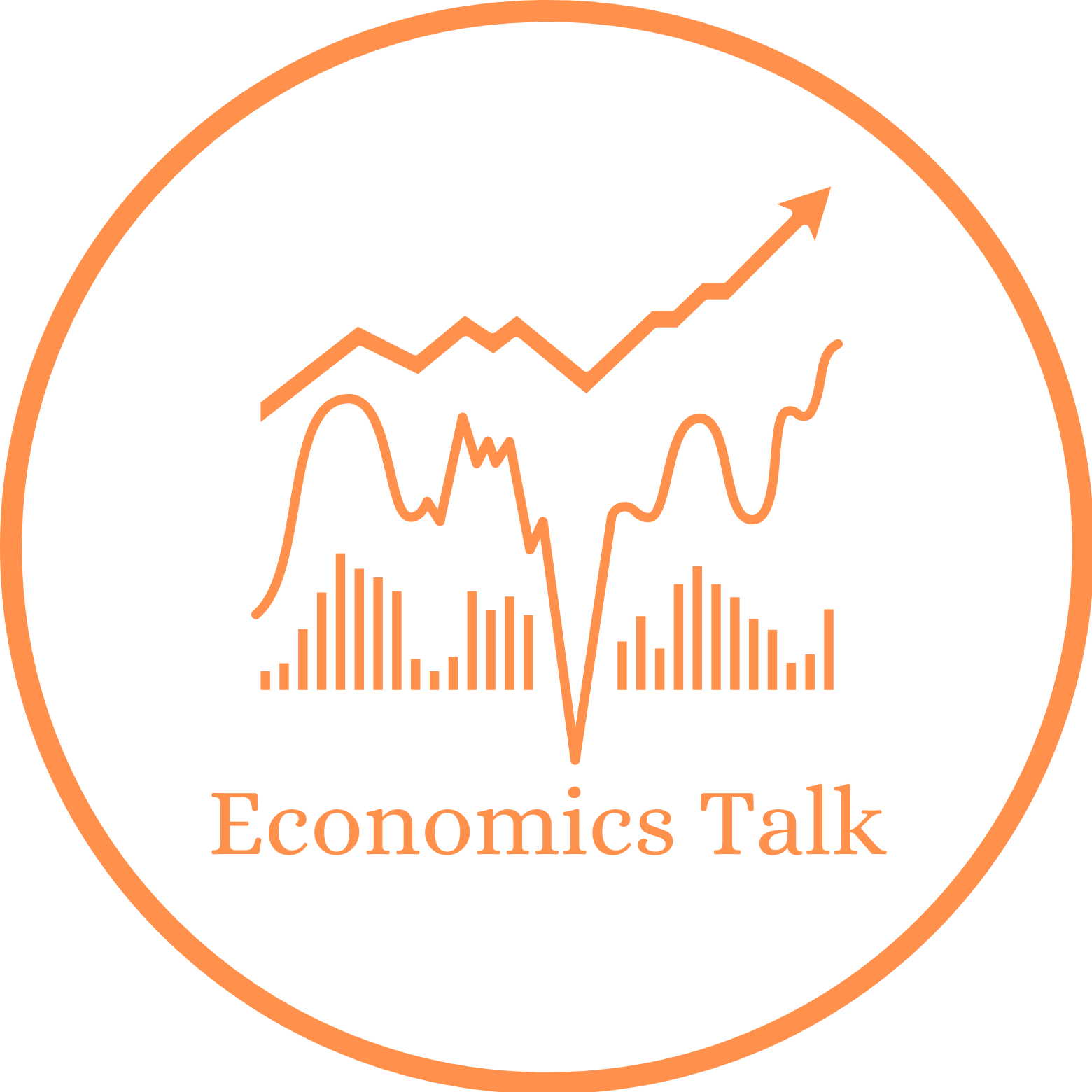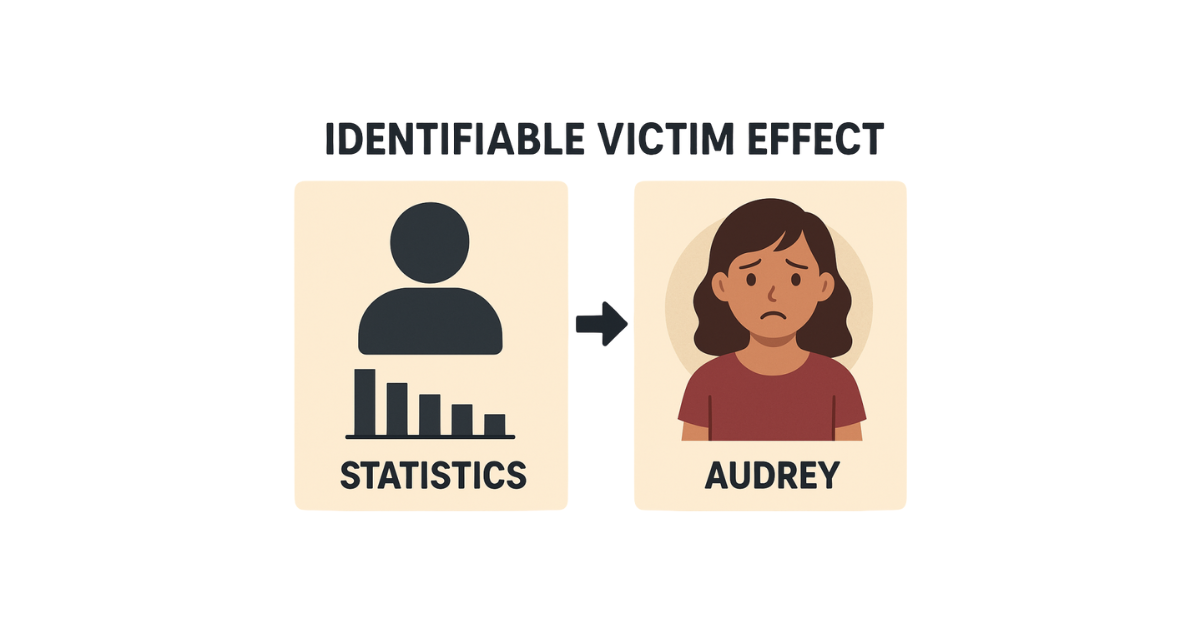Ingatkah kalian dengan kasus pro kontra ditahun 2019 yang bertagar #JusticeForAudrey, bahkan kasus tersebut bertahan selama lebih dari 1 bulan penuh menjadi trending topik pada platform twitter (saat ini menjadi x.com). Kasus tersebut mengundang perhatian dari puluhan influencer, dan bahkan beberapa diantaranya tidak hanya mendukung, tapi datang ke rumahnya. Akan tetapi, 3 bulan kemudian fakta lain muncul yang ternyata pemicu kasus awalnya adalah Audrey itu sendiri dan memunculkan tagar baru #AudreyJugaBersalah, karena ternyata pengeroyokan itu tidak pernah terjadi, dan hasil visumnya pun ternyata janggal dan tidak terbukti sama sekali. Tapi gimana respon masyarakat di Indonesia? di 1 minggu pertama petisi sudah ditanda tangani 3.6juta orang secara online, dan menariknya ratusan juta hingga milyaran sumbangan sudah terkumpul dan diberikan kepada Audrey.
Tapi anehnya, sepanjang tahun di kota yang sama yaitu pontianak, sering terjadi kebakaran hutan dan banjir, tapi kok tidak pernah ada penggalangan dana, tidak ada berita yang viral berbulan-bulan, tidak ada perhatian dari influencer? Lah kok bisa ya respon dan sikap masyarakat berbeda terhadap isu bencana dan kebakaran hutan? kok tidak segetol dan seviral memperjuangkan Audrey itu? padahal kan lokasi sama? korbannya malah lebih banyak, kok malah jarang ada yang membahas dan menyalurkan sumbangan?
Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui identifiable victim effect yang merupakan fenomena di mana orang lebih bersedia membantu individu tertentu yang dapat diidentifikasi daripada kelompok besar orang yang anonim dengan kebutuhan yang sama atau lebih besar. Efek ini berasal dari peningkatan empati dan ikatan emosional terhadap korban tunggal, yang sering kali diperkenalkan dengan detail pribadi seperti nama atau foto. Tapi kok bisa sih hal itu bisa terjadi? ada beberapa preposisi yang menjelaskannya:
Permasalahan Empati dan Emosinal: Orang-orang membentuk ikatan emosional yang lebih kuat dengan individu yang dapat diidentifikasi, sehingga lebih mudah untuk empati terhadap penderitaan mereka. Mereka berpikir bahwa ketika korban yang teridentifikasi merupakan tanggung jawab dari sosial masyarakat. Sedangkan ketiak korbannya masif seperti bencana alam dan kejadian lainnya, mereka berfikir bahwa itu adalah “tanggung jawab pemerintah” dan bukan merupakan tanggung jawab masyarakat.
Persepsi Kemampuan untuk membantu: Bagi masyarakat, ketika mereka memberikan bantuan. Ketika korbannya teridentifikasi mereka “merasa dan percaya” bahwa bantuan mereka dapat berkontribusi dalam mengubah kehidupan korban yang teridentifikasi tersebut dibandingkan dengan korban berkelempok, khususnya jika korbannya tidak teridentifikasi terdapat kecurigaan sumbangan yang mungkin hilang akibat dari moral hazar pengumpul.
Unik banget… dan cukup menarik untuk dibaca yah? Cukup relevan kan kenapa banyak platform donasi lebih suka untuk “memperlihatkan profil dari korban” agar mengambil rasa iba kita… Kira-kira awal studi psikologi tersebut yang dipakai sampai sekarang gimana ya? Bermula dari Jenni & Loewenstein (1997) yang menguji respon orang terhadap permintaan donasi. Ternyata temuannya menunjukkan bahwa partisipan lebih mau berdonasi ketika korban ditampilkan dengan nama dan wajah, dibanding hanya dijelaskan sebagai “satu dari banyak korban.” Kemudian temuan ini dilanjutkan oleh Slovic (2007) yang memperkenalkan permasalah psikologi yang disebut dengan konsep psychic numbing, yaitu semakin besar jumlah korban, semakin “mati rasa” respons emosional manusia.
Fenomena identifiable victim effect pada akhirnya mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga emosional. Kita lebih mudah tersentuh oleh wajah, nama, dan cerita personal dibandingkan angka-angka statistik yang besar dan abstrak. Inilah sebabnya mengapa satu kisah individu bisa menggerakkan lebih banyak donasi, simpati, dan aksi sosial dibandingkan seruan untuk jutaan korban.
Di satu sisi, efek ini bisa dimanfaatkan secara positif oleh lembaga amal atau platform donasi untuk meningkatkan kepedulian sosial. Namun, di sisi lain, kita juga perlu waspada agar empati kita tidak hanya berhenti pada satu individu yang mungkin salah sasaran, melainkan juga mampu meluas pada kelompok besar yang sama-sama membutuhkan.
Jadi, meskipun “satu korban bernama Audrey” mungkin lebih mudah membuat kita tergerak, jangan sampai kita lupa bahwa di balik statistik jutaan korban, ada jutaan cerita yang sama-sama nyata.
Further Reading: